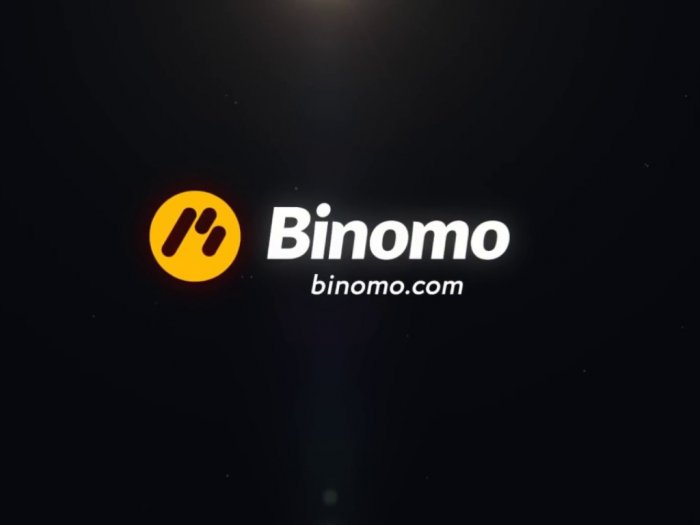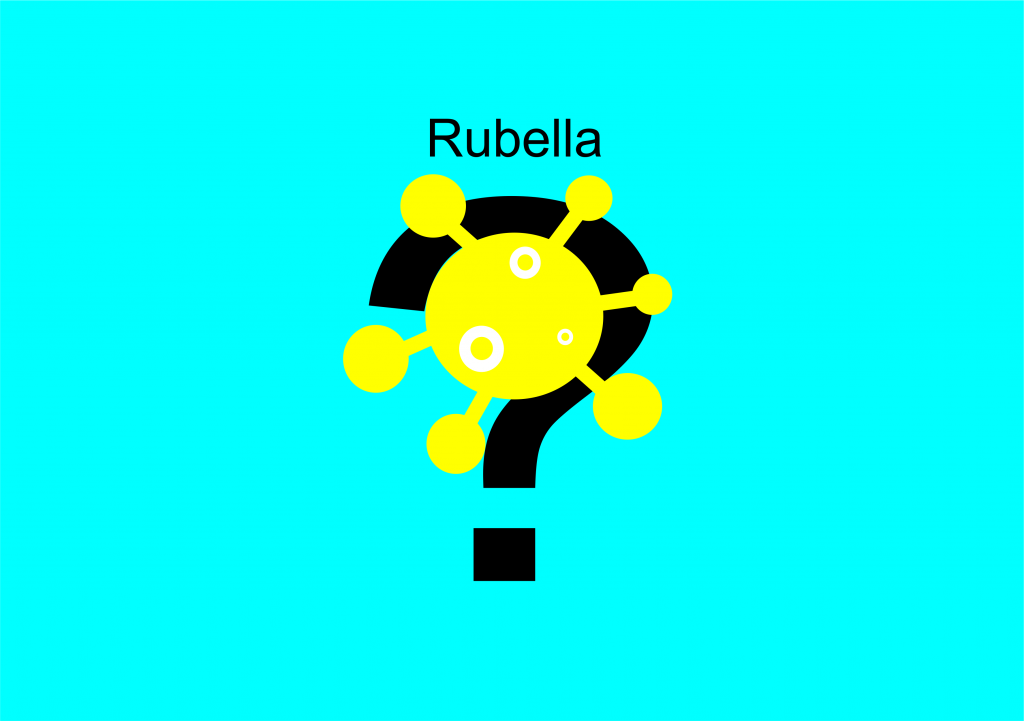Malam itu Aku dan Re duduk di atas bangku halte seberang kampus. Kami baru saja selesai mengikuti Musyawarah Komisariat atau Muskom. Tanpa diduga, sidang berlangsung tidak baik-baik saja dan hal itulah yang membuat kami keluar dan pulang terlebih dahulu. Karena kondisi seperti itu, dirasa sidang akan memakan banyak sekali waktu, sedangkan Aku harus mencuci baju dan menuntaskan tugas-tugas yang banyaknya minta ampun.
Kami meninggalkan Muskom pada saat genting-gentingnya. Saat itu, sidang mulai memasuki agenda penentuan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa. Alasan kami keluar sederhana, yaitu tidak mau pulang dengan keadaan muka bonyok. Hantaman kursi yang melayang kadang terjadi walaupun bukan dialamatkan kepada kami, tetapi mencegah lebih baik bukan? Sambil menunggu angkot yang lewat, kami berbincang-bincang seputar keadaan politik di kampus yang tidak kunjung membaik
Seperti kejadian dahulu, kami melihat peserta yang mulai terpancing emosinya tidak bisa ditenangkan, sehingga pihak keamanan kampus harus turun tangan. Satpam yang kebetulan sedang berjaga-jaga ikut dalam menenangkan peserta sidang. Terlihat mereka seperti sudah siap-siap untuk saling menumpahkan darah saudara seimannya.
Aku langsung berpikir, kalau tidak seiman pun setidaknya mereka bisa memandang lawan politiknya sebagai saudara sekemanusiaan. Walaupun istilah itu memang lebih rumit untuk disebut, setidaknya hal itu mestinya bisa mengingatkan mereka bahwa lawan politiknya pun juga manusia, malah seiman pula. Belum lagi saat itu adalah bulan Ramadhan, yang sepatutnya menjaga emosi.
Waktu sidang, kedua belah pihak berteriak demi nama jurusan yang lebih baik, bagus, dan unggul ke depannya. Namun, kami seperti tidak melihat iktikad baik dari kedua belah pihak yang bertanding untuk memenangkan kursi jabatan tertinggi di Himpunan Jurusan. Hal tersebut sudah nampak dari awal dimulainya sidang. Pembatasan peserta sidang memang terlihat agak ganjil dan diskriminatif terhadap satu golongan. Saya kira hal itu sudah diset sedari awal agar bisa memuluskan langkah salah satu calon yang akan maju agar tetap dari golongan mereka.
“Semua sama saja,” kata Re
“Tidak ada bedanya para anggota anggota Hima dengan para anggota DPR,”
“Mereka sama saja, berteriak atas nama kebaikan dan kepentingan umum tetapi yang ada hanyalah ego golongannya, kepentingan golongannya!!”
“Tetapi setidaknya mereka menunjukkan iktikad baik bukan Re untuk bisa membangun semua kebaikan itu. Walaupun mereka tak jarang disetir oleh golongannya untuk memutuskan A dan B agar menguntungkan mereka.” Pungkasku.
“Tetapi aku sudah tidak percaya dengan mereka. Sudah terlalu banyak kebohongan mereka yang kemudian terungkap secara sendirinya ke khalayak.” tegas Re.
Kemudian Re menceritakan tentang penulis favoritnya asal Argentina, Jorge Luis Borges. Bahwa Borges tua memiliki pemikiran-pemikiran anarkistis yang tidak mempercayai apa saja yang dilakukan oleh negara. Mulai dari sektor birokrasi pelayanan publik, pendidikan, sampai kesehatan. Atau apapun yang berbau pemerintah dan turunan-turunannya. Sampai-sampai Borges memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya di sekolah pemerintah dan memutuskan untuk mengambil alih persoalan pendidikan anak-anaknya di rumah. Borges dan keluarganya sangat akrab dengan perpustakaan dan buku-buku. Sampai segitunya Borges tua tidak mempercayai pemerintah.
“Lalu maksudmu kau juga tidak ingin menyekolahkan anakmu nanti begitu?” Tanyaku kepada Re, gagal paham.
“Bukan begitu, maksudku kita bisa sukses dalam idealisme kita tanpa perlu memikirkan soal perpolitikan itu. Apalagi sampai bergabung ke salah satu golongan yang dominan di kampus. Aku yakin bahwa kita bisa berkembang tanpa perlu bergantung kepada salah satu golongan di kampus ini.”Jawabnya.
Kemudian angkot tiba, dan kami pun beranjak untuk pulang ke kosan masing-masing.
Penulis merupakan mahasiswa semester 4 Sosiologi UIN Bandung