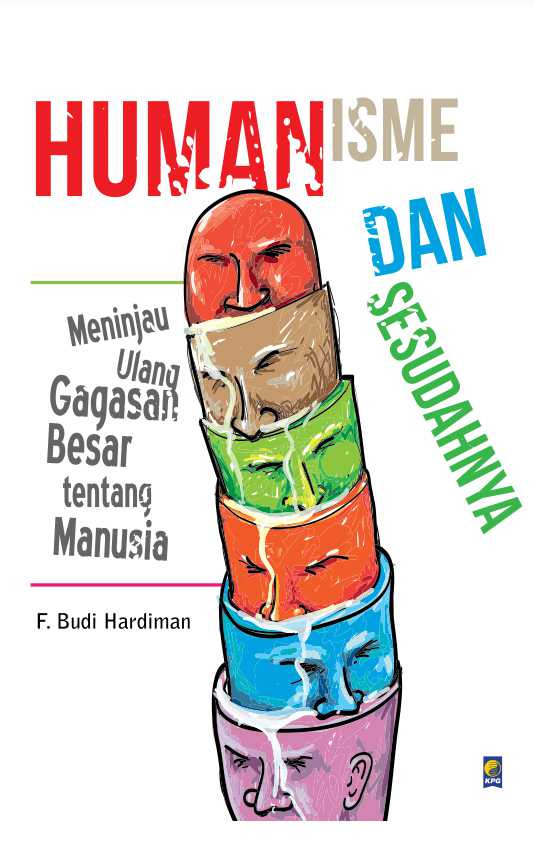JURNALPOSMEDIA.COM – Mungkin banyak dari kita sudah sering bahkan bosan bila sebuah opini selalu mengulas tentang pendidikan. Namun, memang kendala ini yang kerap kali mendapat perhatian dari kalangan akademisi. Mereka mencari tahu lebih dalam apa penyebab jatuhnya prestasi peserta didik sehingga taraf pendidikan jauh di bawah negara-negara maju lainnya.
Anggap Finlandia sebagai negara nomor satu dalam mencanangkan sistem pendidikan yang berkualitas dan mencetak generasi terbaik di lingkup internasional. Pertanyaannya, apakah sistem pendidikan di negara kita yang salah atau faktor lainnya yang menyebabkan edukasi bagai dipandang sebelah mata?
Pada hakikatnya tidak ada yang salah, namun kebanyakan masyarakat Indonesia lebih menganggap pendidikan sebatas mencari pekerjaan. Lalu mendapatkan gelar tinggi sehingga mencapai impian seakan mudah karena yang diharapkannya ada dua: pujian dan uang.
Di titik ini kita boleh menggarisbawahi bahwa pendidikan yang baik bukan dari gelar yang didapat. Namun bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat sekitar yang awam dengan ilmu mutakhir sehingga takkan ada lagi yang kekurangan di sektor pendidikan dan dapat selaras dengan perkembangan zaman.
Berangkat dari hiruk-pikuk akademik yang kita rasa menyebalkan, harus bergelut dengan buku dan mengerjakan tugas dari guru padahal tak ada minat dalam mendalami ilmu tersebut. Maka kita boleh ulas satu per satu sebelum nanti akan dikomparasikan dengan pendidikan global – secara umum. Namun jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pembahasan selanjutnya bisa bermanfaat bagi pembaca budiman dimanapun berada.
Kisah bermula dari monolog saya yang mengkritik pendidikan di negara sendiri. Mungkin akan lebih satire namun berbobot untuk diulas karena menyangkut tragedi penting dalam sistem pembelajaran yang dialami oleh kejadian pribadi.
Suatu pagi yang cerah, saya bersiap masuk ke sekolah tepat pukul 07.00 dan berakhir pada tengah hari, pukul 12.00. Sebuah rutinitas dalam satu minggu yang sangat menjemukan, kecuali hari Minggu. Tas berat berisi buku-buku akademik yang kurasa hanya dibaca saat jadwal pelajaran digelar. Padahal buku itu memuat banyak wawasan penting bila dibaca setiap hari.
Namun, acapkali kita terlalu mengabaikan perintah guru dan tak ada gairah untuk membaca buku. Lebih menyayangkan untuk menghabiskan waktu dalam menggunakan gawai setiap detik, sehingga kita lebih pintar menulis komentar di sosial media daripada mengembangkan ilmu di dunia nyata.
Kecintaan pada buku dan ilmu yang terlalu minim menimbulkan efek negatif pada diri pribadi sehingga mudah menyepelekan sesuatu, padahal isinya bernilai tiada tara. Sebuah pepatah arab mengatakan, “Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti lebih banyak akan menyebutnya.” Sementara, akhir-akhir ini kulihat buku tebal hanya teronggok di rak lemari, dibiarkannya sampai sarang laba-laba menyelimutinya.
Masih di posisi yang sama, di sekolah tercinta kita dibuat jenuh akibat waktu pagi yang dihabisi untuk buka buku dan mengisi absensi harian. Alasannya bahwa otak lebih bekerja keras saat pagi dan lebih konsentrasi untuk menyerap ilmu. Tapi pada faktanya, riset oleh Direktur Pusat Neurosains UHAMKA, Dr. Rizki Edmi Edison Ph.D dalam seminarnya mengatakan bahwasannya waktu untuk berkonsentrasi rata-rata sekitar 20 menit pertama.
Lantas, bagaimana jam-jam yang akan datang? Untuk masalah ini mungkin sangat subjektif. Bila dilihat dari segi pengajar, belajar pada pagi hari dinilai berguna sebagai sarana latihan agar terbiasa menjaga waktu supaya tidak terbuang dengan hal sia-sia.
Murid pun beralasan bahwa dari sekian banyaknya waktu, bahkan malam hari, justru tiada habis untuk mengerjakan PR dan aktifitas di dalam lingkup rumah. Sehingga pertanyaan muncul dari benak mereka, “kapan waktu untuk rehat sejenak, sementara tugas kian menumpuk?”. Begitulah dua kubu yang saling mengungkapkan alibi beragam dan berjalan secara kontinyu, masih saja berkutat dalam ruang sekolah tiada henti.
Hal ini menyangkut antara kewajiban dan hak. Kita lebih banyak menuntut agar hak dipenuhi, namun kewajiban terlihat nihil secara progresif. Sedangkan pendidikan adalah jalur tengah untuk mengetahui di mana posisi kita sebagai peserta didik dan guru sebagai pengajar ilmu.
Banyaknya beban akademik bukan berarti menggagalkan kita dalam memperoleh hak secara maksimal untuk nyaman dari segala tuntutan. Namun ada nilai berharga dibalik bertahun-tahun mengenyam pendidikan dari jenjang ke jenjang, yakni cinta. Sebagaimana ulasan sebelumnya, kurangnya cinta pada pendidikan menjadikannya tak memperoleh sedikit pun dari ilmu kecuali hanya gelar belaka dan kepala kosong – maaf satire.
Misal, kita pernah mencintai seseorang, bahkan setiap hari tidak lupa untuk menanyakan kabar perihal keadaannya. Tapi kalau rasa cinta itu hilang, jangankan bertukar kasih, punya rasa pun tidak. Yang ada hanya menggapainya dalam khayalan semata. Jadi, semakin besar kewajiban maka hak yang diperoleh pun besar jua.
Jangan salahkan guru yang memberi banyak tugas, tapi salahkan kita mengapa tidak bisa mengatur kewajiban semaksimal mungkin. Bukannya dengan cinta, segala urusan jadi ringan? Cinta dilahirkan sebagai indikator betapa besarnya minat kita pada sesuatu. Cinta juga akan lebih besar bila datang langsung ke tempat sumber.
Akankah cinta bisa melekat erat bila mendatangi sumber yang mana sangat kita minati? Disinilah letak di mana kita masih belum bisa bersikap profesional untuk mencintai hal yang hakiki. Sementara kita menjauh dan enggan menyapa guru yang jelas-jelas sebagai sumber ilmu itu sendiri, tidak menghargai guru bahkan melawan segala kebijakan yang berlaku.
Sungguh tidak patut peserta didik untuk bersikap acuh dan sombong pada guru sehingga ilmu serasa sukar larut dalam benak karena mereka tidak sekalipun membuat jalur agar ilmu itu masuk. Seperti gelas kosong di hadapan teko, air tidak akan masuk bila menjauh dari corong teko, dan air jelas tidak tertuang bila letak gelas lebih tinggi daripada teko. Ingat, cinta itu mendekatkan, bersikap patuh adalah bentuk cinta paling dasar dalam mengakrabkan ilmu supaya terkoneksi ke sanubari.
Zaman berganti, kita menjadi lebih dewasa dan sikap seharusnya profesional. Sementara ilmu semakin bertambah, namun bagai tak berguna sebab melenceng jauh dari minat kita sehingga dilupakan lalu hilang tanpa sisa. Rasa perhatian pada ilmu kian surut sedangkan diri kita sudah dijatuhi beberapa problematika orang dewasa pada umumnya. Sehingga lebih fokus untuk mencari pekerjaan dan menghampiri jodoh yang berada di tangan Tuhan.
Padahal, berkat ilmu tidak mungkin kita akan sedewasa ini dan pasti bertingkah layaknya anak kecil yang manja dan ingin terus dipenuhi segala haknya, lagi-lagi ilmu dinomor-duakan.
Sebagai pengajar pula wajib untuk melayani ilmu dengan cinta dan ramah, mengajarkan pada murid dengan lemah lembut. Bukan yang kasar dan ingin dihargai sehingga murid takut untuk berjumpa guru dimanapun berada. Bila dari kedua belah pihak ini saling menjaga cinta, pastikan aliran ilmu itu deras bak air terjun. Tidak hanya itu, konsep pendidikan juga akan berjalan optimal meski disisipi oleh beragam sistem.
Lantas, penyebab utama dari bobroknya pendidikan di Indonesia adalah kurang memahami konsep cinta dalam menyerap ilmu. Kita seperti lentera cinta yang melahirkan simbiosis mutualisme demi keutuhan pendidikan pada generasi mendatang.
Penulis merupakan mahasiswa aktif pada prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Bandung