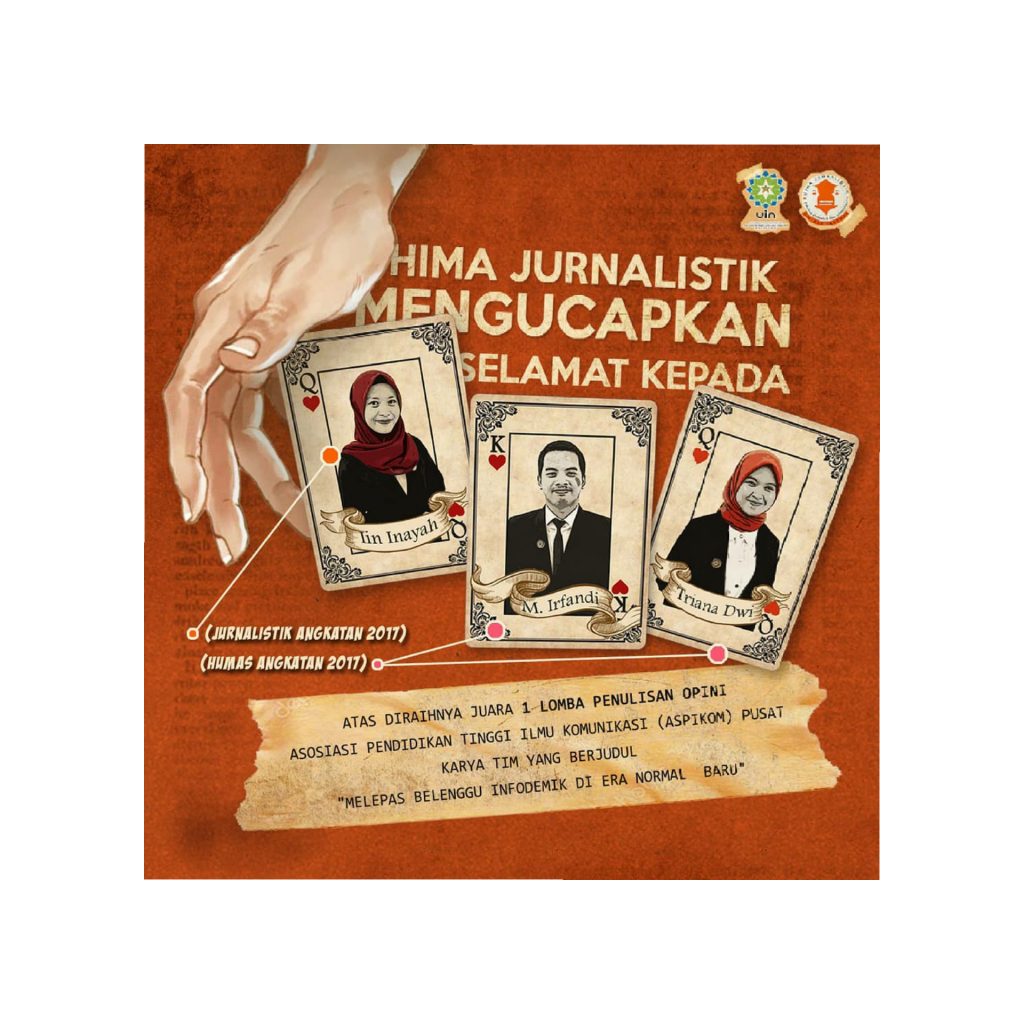JURNALPOSMEDIA.COM – Kebudayaan Rengkong merupakan bagian penting dalam kehidupan Masyarakat Agraris Sunda khususnya di Desa Sirnajaya, Kecamtan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat. Tidak seperti bentuk kesenian lainnya yang cenderung berfungsi sebagai hiburan atau pertunjukan, rengkong sejak awal tumbuh dari aktivitas pertanian masyarakat setempat terutama pada saat panen raya. Keberadaan rengkong tentunya tidak terlepas dari sistem sosial dan spiritual para petani yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap alam.
Kebudayaan Rengkong yang Masih Lestari
Seiring dengan perubahan zaman yang terus bergerak maju, tidak sedikit kebudayaan tradisional (buhun) mulai terpinggirkan dan menghadapi tantangan untuk tetap bertahan di tengah kehidupan masyarakat. Modernisasi, globalisasi, serta pergeseran nilai-nilai generasi muda seringkali menyebabkan warisan budaya terpinggirkan.
Meski begitu, di sejumlah daerah masih ada usaha serius dari masyarakat untuk terus merawat dan melestarikan warisan budaya leluhur. Salah satu contohnya adalah masyarakat Sirnajaya, yang tidak hanya mempertahankan seni rengkong sebagai bentuk warisan budaya tetapi memaknai ulang fungsi dan nilainya sebagai bagian dari identitas dan kebersamaan mereka.
Rengkong bukan sekedar sebuah kesenian pertunjukan biasa. Lebih jauhnya ia merupakan praktik budaya yang lahir dari kehidupan agraris yang berfungsi sebagai sarana pengangkutan padi dari sawah ke leuit (lumbung padi). Alat ini terbuat dari bambu jenis gombong yang ketika digunakan akan menghasilkan bunyi yang berirama, menciptakan suara khas yang menjadi bagian dari lanskap suara panen raya di masa lalu.
Asal-usul Budaya Rengkong
Menurut tradisi lisan masyarakat setempat, pada zaman dahulu rengkong dilakukan tanpa adanya unsur transaksional. Para tukang rengkong (yang memikul padi), bekerja secara sukarela atas dasar niat tulus. Mereka tidak meminta upah, pun sebaliknya pemilik sawah menunjukkan rasa hormat kepada mereka.
Bahkan ada kebiasaan unik pada masa itu, di mana pemilik sawah mengipasi tukang rengkong yang sedang kelelahan. Pemandangan ini tentu sudah jarang ditemui di zaman sekarang. Hubungan timbal balik seperti ini mencerminkan nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang kuat dalam struktur masyarakat pedesaan.
Dalam konteks nilai budaya, rengkong bukan hanya soal mengangkut padi, tetapi juga mengandung penghormatan terhadap alam. Setiap butir padi yang jatuh akan dipungut kembali karena dianggap sebagai rezeki yang tidak boleh disia-siakan.
Kepercayaan masyarakat terhadap Dewi Sri sebagai simbol kesuburan juga menjadi bagian dari narasi rengkong itu sendiri. Dalam hal ini, masyarakat Sirnajaya tidak menyembah, namun menghargai keberadaan simbol tersebut sebagai bentuk spiritualitas lokal.
Budaya Rengkong Menjadi Ruang Ekspresi
Seiring berjalannya waktu, seni rengkong tidak lagi terbatas pada aktivitas pertanian, tetapi turut dihadirkan dalam hajat lembur atau pesta rakyat yang menjadi ruang ekspresi kebudayaan. Pada perayaan tersebut berbagai kesenian tradisional seperti reog, dogdog, dan kendang dihadirkan secara kolaboratif. Makanan yang disajikan pun menggambarkan kearifan lokal, seperti nasi tumpeng, singkong dan ubi, tanpa daging-dagingan yang mencerminkan kesederhanaan dan kedekatan dengan alam.
Peran penting dalam siklus pertanian dan penyelenggaraan tradisi ini dijalankan oleh tokoh adat yang disebut Pertiwi. Ia adalah sosok yang dihormati karena kemampuannya membaca tanda-tanda alam, mengatur jadwal tanam, serta membagi air irigasi secara adil. Bahkan sebelum musim hujan tiba, Pertiwi dapat memperkirakan waktunya berdasarkan gejala alam yang disebut bentang waluku.
Masyarakat melakukan gotong royong dengan sistem kerja kolektif bernama liliuran, yang mencangkup berbagai kegiatan seperti membersihkan selokan, ngabaladah (membersihan sisa tanaman di sekitar tanaman padi), hingga ngangler (meratakan permukaan tanah dan mempersiapkannya untuk bercocok tanam). Hal ini menegaskan adanya sistem sosial ekologis yang teratur, berbasis pengetahuan lokal yang diwariskan lintas generasi.
Kebangkitan Budaya Rengkong
Kebangkitan rengkong di Sirnajaya dimulai kembali pada tahun 2007, ketika salah satu tokoh masyarakat yaitu Abah Iri Sahri diundang oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk menampilkan seni tradisional dalam suatu acara kebudayaan. Meski saat itu belum mengenai secara utuh tradisi ini, Abah Iri kemudian mencari informasi ke berbagai kecamatan di Bandung Barat, yaitu Kecamatan Rongga, Kecamatan Cipongkor, Kecamatam Sindangkerta hingga Kecamatan Gununghalu dan menemukan fakta bahwa seni rengkong memiliki akar kuat di Kampung Cicurug, Desa Sirnajaya.
Dalam praktiknya, bambu yang dipakai untuk membuat alat rengkong bukanlah sembarang bambu. Pada jaman dahulu, hanya bambu gombong yang tumbuh di kawasan Leuweung Salawe Jajar yang dapat digunakan. Masyarakat percaya bahwa bambu yang cocok dan ‘berjodoh’ untuk menjadi bagian dari rengkong apabila bambu tersebut menghasilkan bunyi yang khas ketika dimainkan.
Budaya Rengkong yang Terus Meluas
Sejak pertama kali ditampilkan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabutapen Bandung Barat (KBB) yang pertama pada tahun 2008, rengkong Sirnajaya mulai dikenal luas. Kesenian ini sering hadir pada acara resmi, seperti penyambutan pejabat pemerintahan, hajat lembur, maupun festival budaya.
Meski demikian, masyarakat Sirnajaya tetap menjaga keaslian nilai-nilai dalam praktiknya. Rengkong tidak diperjualbelikan serta tidak ada sistem bayaran dalam pementasan. Semua dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur serta rasa cinta terhadap budaya.
Keunikan rengkong Sirnajaya dibanding daerah lain terletak pada kedalaman nilai budayanya. Selain dipentaskan pada festival, rengkong Sirnajaya juga menjadi bagian dari kehidupan bersama, yang berlandaskan sukarela, gotong royong dan penghormatan terhadap ritme alam. Tak heran, banyak orang yang awalnya tidak tertarik justru terkesan setelah menyaksikannya secara langsung, seakan seni ini memiliki kekuatan batiniah yang dapat menyentuh siapa saja.
Pelestarian rengkong di Sirnajaya menjadi bentuk perlawanan halus terhadap arus globalisasi yang sedikit demi sedikit mengikis nilai-nila lokal. Dengan mempertahankan kebudayaan ini, masyarakat Sirnajaya bukan hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga mempertahankan cara hidup yang menghargai alam, menjungjung kebersamaan, serta memahami makna rezeki dalam kesederhanaan. Bagi masyarakat Sirnajaya, rengkong adalah identitas yang harus dirawat, diperkenalkan, dihargai dan dilestarikan.